Pada awal 1970-an, seorang konsultan muda asal Amerika bernama John Perkins mendarat di Jakarta. Ia bukan diplomat, bukan tentara, bukan pula investor besar. Ia datang dengan jas rapi dan proposal-proposal pembangunan yang tampak menjanjikan. Namun di balik itu semua ia membawa sebuah misi yang kelak ia sebut sebagai pekerjaan seorang economic hitman. Perkins bekerja untuk perusahaan konsultan teknik Amerika yang ditugaskan menyusun studi kelayakan proyek infrastruktur di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Proyek itu dibiayai dengan pinjaman luar negeri yang nilainya sangat besar. Logikanya sederhana, negara-negara berkembang diberi pinjaman atas nama pembangunan, tapi sebenarnya dibuat agar mereka berutang sedemikian besar sehingga tak bisa melepaskan diri dari kendali politik dan ekonomi negara donor. Indonesia, dengan sumber daya alam berlimpah dan posisi strategis di Asia Tenggara menjadi target empuk apalagi setelah kejatuhan Sukarno dan naiknya Soeharto diaman Amerika Serikat melihat peluang emas untuk menjadikan Indonesia sekutu baru.
Mengapa Indonesia Jadi Target
Indonesia tahun 1970-an baru saja melewati pergolakan politik besar pada Rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto membuka diri pada modal asing termasuk pinjaman dari Bank Dunia, IMF, dan lembaga keuangan Barat. Bagi John Perkins dan rekan-rekannya, inilah ladang subur. Indonesia dijual pada dunia internasional sebagai negara dengan “potensi besar” yang hanya perlu sedikit bantuan modal untuk menjadi macan Asia. Bantuan itu tentu saja berbentuk pinjaman luar negeri. Pinjaman yang seolah-olah untuk membiayai listrik, jalan raya, bendungan, dan proyek pembangunan lainnya. Namun, seperti diceritakan Perkins, di balik proyek-proyek itu ada misi lain yaitu membuat Indonesia tergantung pada utang, sehingga pemerintah tidak punya banyak pilihan selain mengikuti kebijakan yang menguntungkan donor dan perusahaan asing.
Jejak Utang Publik Indonesia
Data berbicara dengan jelas pada akhir 1960-an total utang luar negeri Indonesia hanya sekitar US$ 2 miliar namun angka itu melonjak pesat di era 1970-an dan 1980-an, terutama karena proyek infrastruktur dan eksploitasi energi yang dibiayai pinjaman. Masuk ke era 1990-an, utang semakin menumpuk. Krisis 1997–1998 menjadi puncak dan Indonesia dipaksa tunduk pada program bailout IMF yang menjerat ekonomi dalam paket reformasi struktural. Lagi-lagi, utang menjadi pintu masuk kontrol eksternal. Kini utang masih menjadi bagian penting dari keuangan publik kita. Per 2025, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 9.105 triliun setara sekitar 39% Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini memang masih dalam batas aman menurut standar internasional, tetapi tetap menimbulkan pertanyaan besar sampai kapan APBN kita harus bergantung pada pinjaman?
Utang dan APBN
Dalam logika fiskal modern utang dianggap instrumen sah untuk menutup defisit anggaran. Pemerintah berutang agar tetap bisa membiayai pembangunan ketika penerimaan pajak tidak mencukupi. Namun persoalannya bukan sekadar “utang atau tidak utang” melainkan bagaimana utang itu dikelola dan untuk apa digunakan. Mari kita lihat struktur APBN setiap tahun, porsi besar dari belanja negara dialokasikan hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang. Pada 2024 misalnya pembayaran bunga utang mencapai lebih dari Rp 500 triliun, jumlah yang hampir setara dengan anggaran kesehatan nasional artinya sebagian besar uang pajak rakyat tidak kembali dalam bentuk layanan publik melainkan untuk membayar kewajiban ke kreditur inilah yang dimaksud John Perkins dengan “jerat” economic hitman. Utang yang semula diklaim untuk pembangunan akhirnya mengikat negara, membatasi ruang fiskal, dan memaksa pemerintah menyesuaikan kebijakan agar tetap bisa mengakses pinjaman baru.
Antara Realitas Pembangunan dan Ilusi
Tentu saja, tidak semua utang itu sia-sia jika kita melihat jalan tol, bendungan, pembangkit listrik, dan infrastruktur lainnya yang berdiri berkat pinjaman luar negeri namun pertanyaan kritisnya apakah manfaatnya sepadan dengan beban fiskal jangka panjang? Sejumlah proyek di masa lalu terbukti tidak efektif, bahkan mangkrak, lebih dari itu banyak proyek justru dirancang agar menguntungkan kontraktor dan konsultan asing bukan rakyat Indonesia. Kondisi ini masih terasa hingga sekarang meski pemerintah gencar membangun infrastruktur, utang tetap membengkak dan penerimaan negara sering kali tidak cukup menutup belanja sementara pajak kita belum optimal akhirnya pola klasik terus berulang pembangunan dibiayai utang, cicilan dibayar dengan pajak, lalu pemerintah kembali berutang untuk menutup kekurangan.
Dalam Bayang-Bayang Economic Hitman
John Perkins menulis bahwa tugas utamanya sebagai EH adalah membuat proyeksi ekonomi yang sengaja dilebih-lebihkan. Ia menghitung seakan-akan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat tinggi jika proyek infrastruktur dibiayai pinjaman. Dengan demikian Indonesia “terpaksa” berutang padahal proyeksi itu tidak realistis. Hari ini, meski bentuknya lebih modern, logika yang sama masih bekerja akan negara-negara berkembang didorong untuk mengambil pinjaman demi mengejar pembangunan melalui lembaga internasional dan investor global yang masih memegang kendali besar. Apakah ini berarti Indonesia sepenuhnya korban EH? Tidak sesederhana itu. Pemerintah memiliki kendali atas kebijakan fiskal dan utang bisa menjadi instrumen produktif jika dikelola dengan baik namun pelajaran dari masa lalu jelas memperlihatkan utang bisa menjadi alat kontrol politik bukan sekadar instrumen ekonomi.
Penutup
Utang publik bukan dosa tapi juga bukan sesuatu yang bisa diabaikan ia ibarat pedang bermata dua yang bisa membangun tetapi bisa juga menjerat. Kisah economic hitman mengingatkan kita bahwa di balik pinjaman luar negeri sering kali ada kepentingan geopolitik yang lebih besar daripada sekadar angka pembangunan. Bagi Indonesia tantangannya adalah bagaimana memastikan fiskal dikelola untuk kepentingan rakyat bukan untuk melayani kepentingan kreditur atau elite tertentu. Dalam hal ini dengan adanya transparansi, akuntabilitas, dan keberanian menolak pinjaman yang tidak bermanfaat memiliki peran penting.
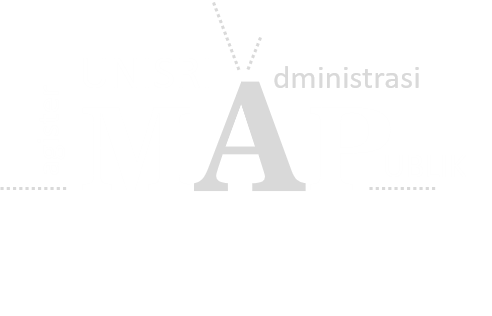


Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.