Apakah negara bisa melakukan kekerasan melalui kebijakan? Pertanyaan ini semakin relevan ketika kita menyaksikan bagaimana berbagai kebijakan publik di Indonesia justru menimbulkan penderitaan bagi masyarakat, alih-alih menyelesaikan persoalan. Dalam kasus tertentu, kekerasan negara hadir dalam bentuk yang lebih halus, tersembunyi, dan dilegitimasi melalui perangkat hukum dan kebijakan publik. Ia menjadi kekerasan yang tidak terlihat (invisible violence), tapi dampaknya nyata dan menghantam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya mereka yang berada di posisi paling rentan.
Di balik meja-meja rapat yang steril atau di balik tumpukan dokumen kebijakan yang tampak netral, negara bisa menjalankan kekuasaan yang mencederai. Kebijakan publik yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan sosial kerap menjadi alat dominasi dan represi. Ia bisa mencabut hak atas tanah, membatasi ruang ekspresi, mengkriminalisasi pembela lingkungan, atau mengabaikan hak-hak kelompok adat, perempuan, dan buruh. Lebih parah lagi, semua itu dilakukan dengan stempel legalitas.
Dalam konteks inilah penting untuk menelaah bagaimana kekerasan negara bekerja melalui kebijakan publik. Kekerasan ini bukan hanya soal fisik, melainkan juga struktural dan simbolik. Ia terjadi ketika kebijakan lahir tanpa partisipasi rakyat, ketika peraturan dibuat untuk melanggengkan ketimpangan, dan ketika negara menggunakan hukum sebagai alat kendali, bukan perlindungan.
Artikel ini mencoba membedah wajah lain dari kekerasan negara bukan melalui laras senjata, tetapi melalui bagaimana kebijakan publik yang bisa menjadi instrumen kekuasaan yang menindas, dan bagaimana seharusnya negara bertindak untuk menciptakan kebijakan yang adil, partisipatif, dan bebas dari unsur kekerasan terselubung.
Tragedi kampung Kampung Pulo dan Bukit Duri
Salah satu kasus kekerasan negara dalam bentuk kebijakan terjadi saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penggusuran terhadap permukiman warga di bantaran sungai atau kawasan yang dianggap ilegal. Misalnya, penggusuran di Kampung Pulo (2015) dan Bukit Duri (2016). Tindakan ini dijalankan dengan dalih penataan kota dan pengendalian banjir meskipun didasarkan pada kebijakan tata ruang dan legalitas hukum, penggusuran dilakukan dengan kekuatan aparat, minim partisipasi warga, dan tanpa skema relokasi yang manusiawi. Banyak warga kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Mahkamah Agung bahkan menyatakan bahwa penggusuran Bukit Duri melanggar hukum dan warga berhak atas ganti rugi. Ini menunjukkan bagaimana kebijakan publik meskipun legal secara administratif tetapi dapat menjadi kekerasan struktural jika mengabaikan prinsip keadilan sosial dan hak warga atas kota
Konseptualisasi Kekerasan Negara
Kekerasan negara dapat dipahami sebagai penggunaan kekuasaan oleh lembaga negara—baik secara langsung maupun tidak langsung—yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, atau struktural terhadap warga negara. Johan Galtung (1969) membedakan antara kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kekerasan struktural terjadi ketika institusi sosial atau kebijakan publik menciptakan ketimpangan dan penderitaan sistemik, tanpa adanya aktor yang terlihat secara eksplisit.
Kebijakan Publik sebagai Instrumen Kekerasan Struktural
Melalui kebijakan publik, negara menjalankan kekuasaan dalam bentuk yang lebih subtil dan sistematis. Dalam konsep Michel Foucault, ini adalah bagian dari biopolitik melalui pengaturan kehidupan warga melalui norma dan regulasi. Kekuasaan tidak lagi hanya represif, tetapi juga produktif dalam menciptakan kepatuhan melalui mekanisme administratif. Kebijakan publik seharusnya berfungsi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan dan perlindungan sosial, Namun dalam praktiknya, kebijakan dapat dijadikan alat reproduksi kekuasaan, pengendalian sosial, dan bahkan represi hal ini terjadi ketika kebijakan dirancang tanpa partisipasi publik yang bermakna, Mengabaikan prinsip keadilan sosial dan hak asasi, ditetapkan untuk melayani kepentingan elit politik atau korporasi tertentu.
Membangun Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative governance framework) adalah jalan keluar
Pertanyaannya, bagaimana kita dapat keluar dari siklus kekerasan struktural yang dilegalkan ini? Salah satu jawabannya adalah dengan mengadopsi pendekatan collaborative governance (Ansell dan Gash 2007: 228). Sebuah kerangka tata kelola kolaboratif yang menekankan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan.
Model ini mengedepankan empat prinsip utama yaitu :
- Face to Face Dialogue
Dialog langs1ung antara aktor-aktor utama kebijakan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang jujur, mendalam, dan mengurangi distrust antar pihak. Konflik sosial yang selama ini ditangani secara koersif dapat dikonversi menjadi arena deliberatif.
- Trust Building
Kolaborasi hanya dapat berjalan jika ada kepercayaan hal ini membutuhkan keterbukaan pemerintah untuk menerima kritik dan transparansi dalam membagikan informasi kepada publik, termasuk draft regulasi dan dokumen pendukung.
- Shared Understanding and Commitment to Common Goals
Kekerasan struktural kerap terjadi karena negara dan masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai “masalah publik”. Kolaborasi memungkinkan terbentuknya kesepahaman bersama (shared problem definition) dan tujuan bersama (co-defined goals).
- Intermediate Outcomes and Adaptive Governance
Proses kolaboratif memungkinkan terciptanya kebijakan yang adaptif terhadap konteks lokal dan perubahan sosial. Ini menghindari kebijakan yang kaku dan represif karena didesain secara top-down.
Penutup
Kekerasan negara dalam kebijakan publik adalah bentuk represi yang sering kali tidak disadari, karena bekerja melalui regulasi yang tampak sah namun menindas secara substansi. Ketika proses penyusunan kebijakan tertutup, elitis, dan mengabaikan suara mereka yang terdampak, maka hukum kehilangan fungsi etiknya dan berubah menjadi alat dominasi. Pendekatan tata kelola kolaboratif (collaborative governance) menawarkan jalan keluar dari pola relasi kuasa yang timpang ini. Dengan mendorong dialog lintas aktor, membangun kepercayaan, dan memastikan partisipasi publik yang sejati, kebijakan dapat menjadi ruang negosiasi dan solusi, bukan arena represi.
Demokrasi tidak hanya diukur dari ada tidaknya pemilu, tetapi dari cara kekuasaan dijalankan dan siapa yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Maka sudah saatnya kita membangun tata kelola kebijakan yang inklusif, adaptif, dan adil—agar hukum tidak lagi menjadi sumber kekerasan, melainkan instrumen keadilan sosial.
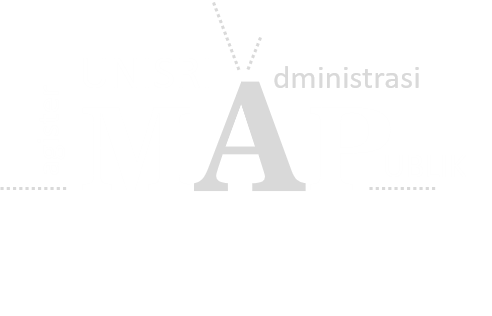

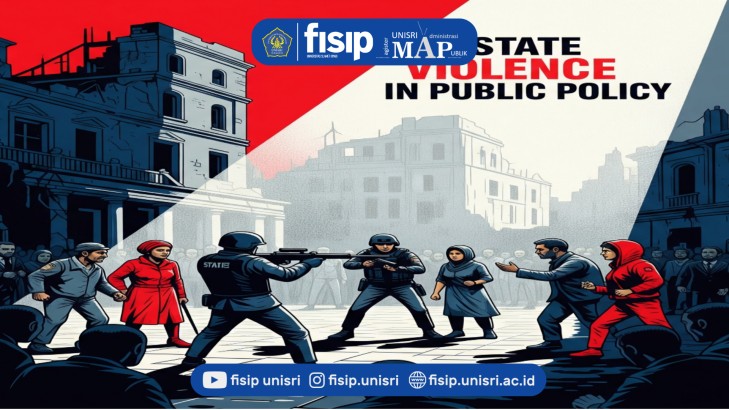
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.