Isu krisis lingkungan di Indonesia mulai dari degradasi hutan, konflik agraria, krisis air perkotaan, hingga kerentanan iklim sering diperlakukan sebagai persoalan teknis-ekologis semata. Pemerintah merespons dengan menambah regulasi, memperkuat standar AMDAL, atau meluncurkan program hijau berbasis proyek. Namun, fakta di lapangan menunjukkan paradoks akan regulasi bertambah, institusi dibentuk, tetapi kualitas lingkungan terus menurun.
Di sinilah konsep Ecological–Institutional Governance (EIG) menjadi relevan. EIG menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan bukan hanya persoalan ekosistem alam, melainkan juga kualitas institusi, relasi kekuasaan, serta cara negara mengelola kewenangan dan insentif kebijakan.
Memahami Ecological–Institutional Governance
Ecological–Institutional Governance berpijak pada gagasan bahwa lingkungan dan institusi saling membentuk (co-evolving). Kerusakan lingkungan bukan sekadar akibat eksploitasi sumber daya, melainkan hasil dari desain kelembagaan yang sektoral dan terfragmentasi, Logika pembangunan yang bias pertumbuhan ekonomi, dan Ketimpangan relasi aktor dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif ini, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi sebagai institutional architect yang menentukan bagaimana kepentingan ekologis dinegosiasikan dengan kepentingan ekonomi dan politik.
Ketika Ekologi Selalu Kalah oleh Kepentingan Ekonomi
Pendekatan pembangunan nasional masih menempatkan lingkungan sebagai faktor yang bisa dinegosiasikan. Ekologi dihitung sepanjang tidak mengganggu target investasi, pertumbuhan, dan proyek strategis. Ketika terjadi konflik antara daya dukung lingkungan dan kepentingan ekonomi, pilihan kebijakan hampir selalu berpihak pada yang terakhir. Inilah yang oleh pendekatan Ecological–Institutional Governance dipahami sebagai kegagalan institusional. Negara memiliki perangkat ekologis, tetapi institusinya tidak bekerja secara ekologis.
Kasus Banjir Perkotaan Ibarat Tata Ruang Tanpa Tata Kelola
Banjir di kawasan Jabodetabek, Semarang, dan sejumlah kota pesisir bukan lagi semata akibat curah hujan ekstrem. Berbagai kajian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan, reklamasi, dan pembangunan kawasan komersial di daerah resapan air menjadi faktor dominan. Masalahnya, keputusan tata ruang tersebut bukan diambil tanpa prosedur, melainkan melalui proses formal yang sah secara administratif. Di sinilah paradoksnya, secara institusional legal, tetapi secara ekologis destruktif. Lingkungan tidak gagal karena tidak dilindungi, tetapi karena tidak dijadikan dasar utama pengambilan keputusan.
Konflik Agraria dan Ekstraksi Sumber Daya
Konflik agraria di wilayah tambang, perkebunan besar, dan kawasan hutan menunjukkan pola yang konsisten. Negara hadir kuat dalam memberikan izin, tetapi lemah dalam memastikan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Dalam banyak kasus, institusi ekonomi dan perizinan bekerja lebih efektif dibanding institusi pengawasan lingkungan. Dampaknya, masyarakat lokal menghadapi degradasi ruang hidup, sementara kerusakan lingkungan diperlakukan sebagai externality yang tidak masuk dalam perhitungan kinerja institusi publik. Ini bukan sekadar konflik sumber daya, melainkan konflik tata kelola.
Pesisir dan Pulau Kecil Adalah Ekologi yang Terpinggirkan
Kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil akibat aktivitas ekstraktif dan pembangunan skala besar juga memperlihatkan kelemahan tata kelola ekologis. Wilayah yang secara ekologis rentan justru menjadi sasaran proyek ekonomi intensif. Kelembagaan negara gagal membaca ekologi sebagai batas (ecological limits), dan sebaliknya memperlakukannya sebagai ruang kosong yang siap diisi oleh investasi. Ketika kerusakan terjadi, tanggung jawabnya terfragmentasi terhadap siapa pun bisa berwenang, tetapi tak satu pun benar-benar bertanggung jawab.
Regulasi Bukan Masalah Utama
Berbagai krisis tersebut memperlihatkan bahwa menambah aturan bukan solusi utama. Indonesia tidak kekurangan kebijakan lingkungan. Yang kurang adalah institusi yang memiliki akuntabilitas ekologis.
Indikator keberhasilan birokrasi masih bertumpu pada penyerapan anggaran percepatan proyek, dan kemudahan investasi. Sementara kualitas lingkungan hidup jarang menjadi ukuran kegagalan atau keberhasilan institusi publik. Selama kerusakan lingkungan tidak berdampak pada evaluasi kinerja, maka secara rasional institusi tidak memiliki insentif untuk berubah.
Lingkungan sebagai Ukuran Mutu Pemerintahan
Ecological–Institutional Governance menuntut perubahan cara pandang yang fundamental. Lingkungan tidak boleh lagi diposisikan sebagai isu sektoral, melainkan sebagai indikator kualitas pemerintahan. Negara yang institusinya kuat seharusnya mampu menahan diri dari keputusan yang merusak daya dukung ekologis, menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan, serta menjadikan kerusakan lingkungan sebagai bentuk kegagalan kebijakan, bukan sekadar risiko pembangunan.
PenutupKrisis lingkungan yang terus berulang seharusnya dibaca sebagai sinyal kegagalan tata kelola, bukan sekadar tantangan teknis. Selama institusi publik tidak menjadikan ekologi sebagai prinsip pengambilan keputusan, pembangunan akan terus berlangsung dengan ongkos lingkungan yang semakin mahal. Pada titik ini, pertanyaan mendasarnya bukan lagi bagaimana membangun, tetapi bagaimana negara mengelola dirinya sendiri agar pembangunan tidak menghancurkan fondasi kehidupan.
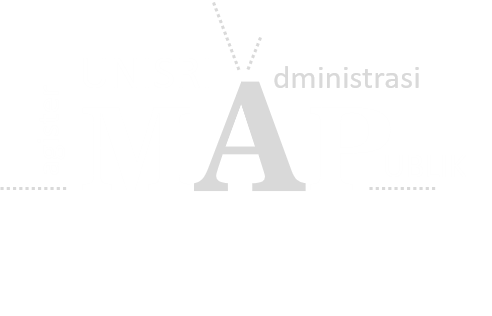


Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.