Setiap tahun pemerintah Indonesia mengelola anggaran negara yang jumlahnya mencapai ribuan triliun rupiah. Anggaran ini baik dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya adalah instrumen vital yang digunakan untuk membiayai pembangunan, memperluas layanan publik, serta menjamin kesejahteraan rakyat. Namun di balik angka fantastis itu terselip pertanyaan besar yang selalu menghantui, sejauh mana uang negara benar-benar sampai ke masyarakat dan sejauh mana ia berdampak melalui praktik korupsi?. Fenomena ini bukan hal baru sejarah panjang pembangunan Indonesia menunjukkan bahwa keuangan publik sering menjadi “ladang subur” bagi praktik korupsi melalui pengadaan barang dan jasa, alokasi dana bansos, hingga proyek infrastruktur strategis berpotensi terjadinya penyelewengan anggaran/dana publik terdapat transparansi yang belum optimal, lemahnya pengawasan, dan tingginya asimetri informasi antara pemerintah sebagai pengelola anggaran dan masyarakat sebagai pemilik sah anggaran, membuka ruang lebar bagi praktik kecurangan.
Di sisi lain globalisasi informasi membuat masyarakat semakin kritis. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia yang masih relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir menjadi cermin bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penindakan hukum untuk memahami itu diperlukan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk memahami akar masalah korupsi dalam keuangan publik yang sekaligus menawarkan solusi kelembagaan. Namun menurut Herbert Simon dalam karya Administrative Behavior pengambilan keputusan birokratis harus dibangun atas dasar ilmu, data, dan transparansi agar agent bertindak akuntabe. Vincent Ostrom memperluas pendekatan ini dengan menawarkan desain administrasi yang polycentric di mana kekuasaan didistribusikan sehingga partisipasi dan kontrol lebih merata, mengurangi peluang penyalahgunaan oleh agent. Secara konkret Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerapkan sistem akuntabilitas melalui laporan LAKIP yang terbuka, sehingga publik dapat menilai sejauh mana lembaga berhasil memenuhi target kinerja yang dibebankan sebagai mandate publik Tema “Menebar Benih Antikorupsi” dalam Laporan Tahunan 2022 menggarisbawahi kerangka preventif dan edukatif yang merupakan langkah struktural melawan moral hazard agent.
(https://cms.kpk.go.id/storage/4205/Laporan-Tahunan-KPK-2022.pdf)
Dalam konteks inilah teori principal–agent menjadi sangat relevan untuk digunakan. Teori ini dapat menjelaskan mengapa praktik korupsi kerap muncul dalam pengelolaan anggaran publik, bagaimana relasi kekuasaan dan informasi antara rakyat dan pemerintah menciptakan celah moral hazard, serta strategi apa yang dapat ditempuh untuk menutup celah tersebut. Dengan menggunakan perspektif ini mencoba menguraikan keterkaitan antara keuangan publik dan korupsi di Indonesia, sekaligus menghadirkan analisis kritis mengenai strategi perbaikan tata kelola keuangan negara. (https://sustain.id/2025/02/20/naik-3-skor-indeks-persepsi-korupsi-cpi-indonesia-tahun-2024-masih-tetap-buruk/#:~:text=Pada%20tahun%202024%2C%20Skor%20CPI,total%20180%20negara%20yang%20disurvei.)
Analisis dampak keuangan publik terhadap praktik korupsi melalui perspektif teori principal–agent
Dalam studi administrasi publik dan ekonomi politik salah satu teori yang paling relevan untuk menjelaskan hubungan antara rakyat, pemerintah, dan pengelolaan keuangan publik adalah teori principal–agent. Teori ini pada dasarnya menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak yang memberi mandat (principal) dengan pihak yang diberi mandat (agent). Dalam konteks keuangan publik di Indonesia, rakyat dapat diposisikan sebagai principal yang memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah sebagai agent untuk mengelola sumber daya keuangan negara.
Rakyat sebagai principal
Principal dalam hubungan ini adalah warga negara yang memiliki hak konstitusional atas sumber daya keuangan negara sepert pajak, retribusi, serta berbagai jenis penerimaan negara merupakan kontribusi masyarakat yang pada dasarnya ditujukan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyediaan pelayanan publik. Dengan demikian, rakyat memiliki ekspektasi bahwa dana publik tersebut dikelola secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Pemerintah sebagai agent
Sebaliknya, pemerintah berperan sebagai agent yang diberi mandat melalui mekanisme demokrasi untuk mengelola keuangan publik. Dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi seperti Indonesia, mandat ini tidak hanya dipegang oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tugas utama agent adalah memastikan bahwa alokasi dan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sekaligus menjamin bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat.
Asimetri informasi dan moral hazard
Permasalahan utama yang muncul dalam hubungan principal–agent adalah adanya asimetri informasi. Dalam konteks keuangan publik rakyat tidak memiliki informasi yang lengkap dan mendetail mengenai bagaimana anggaran negara disusun, dialokasikan, dan direalisasikan. Sebaliknya, pejabat publik sebagai agent memiliki informasi yang jauh lebih luas dan mendalam mengenai proses anggaran. Perbedaan akses informasi ini menimbulkan potensi terjadinya moral hazard, yaitu kecenderungan agent bertindak menyimpang dari kepentingan principal untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Fenomena ini tercermin dalam banyak kasus korupsi keuangan publik di Indonesia. Misalnya, kasus penyelewengan dana bantuan sosial Covid-19 yang melibatkan pejabat publik. Dalam kasus tersebut, pejabat memiliki kontrol penuh atas informasi alokasi dan distribusi bantuan sementara masyarakat penerima manfaat tidak memiliki akses yang setara. Akibatnya sebagian dana publik tidak sampai kepada rakyat melainkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi melalui praktik suap dan mark-up anggaran.
Implikasi terhadap tata kelola keuangan publik
Korupsi yang lahir dari hubungan principal–agent yang tidak seimbang membawa dampak serius terhadap tata kelola keuangan publik yaitu dampak secara ekonomi pada setiap rupiah yang dikorupsi mengurangi kapasitas negara dalam menyediakan layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kemudian secara politik, praktik korupsi merusak legitimasi pemerintah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Selanjutnya secara sosial, korupsi memperdalam ketidakadilan karena kelompok yang paling rentan justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat berkurangnya akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas.
Pengambilan keputusan birokratis dan administrasi polycentric dalam Kerangka Principal–Agent
Teori principal–agent menegaskan bahwa masalah utama dalam tata kelola publik terletak pada asimetri informasi antara rakyat (principal) dan pejabat publik (agent). Untuk mengurangi potensi penyimpangan, diperlukan tata kelola yang memastikan proses pengambilan keputusan berlangsung secara rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka ini, gagasan Herbert A. Simon dalam Administrative Behavior (1947) menjadi tepat. Simon menekankan bahwa pengambilan keputusan birokratis harus dibangun atas dasar ilmu pengetahuan, data empiris, serta prinsip transparansi agar setiap keputusan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga akuntabel. Prinsip ini sejalan dengan upaya mengurangi agency loss, karena ketika keputusan berbasis data dan keterbukaan, ruang bagi agent untuk bertindak menyimpang semakin sempit. Transparansi data anggaran, misalnya melalui e-budgeting dan open government data, merupakan contoh nyata penerapan pendekatan Simon dalam konteks keuangan publik modern. Sementara itu, Vincent Ostrom melalui gagasan administrasi polycentric (1998) memperluas pendekatan ini dengan menekankan pentingnya distribusi kekuasaan dalam tata kelola publik. Menurut Ostrom, kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan sedikit agent menciptakan risiko besar bagi penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, jika kekuasaan dan otoritas didistribusikan ke banyak pusat pengambilan keputusan (polycentric governance), maka partisipasi masyarakat akan meningkat dan mekanisme kontrol menjadi lebih merata. Dalam konteks keuangan publik, model ini dapat diwujudkan melalui mekanisme partisipatif dalam perencanaan anggaran, keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi APBD, serta audit publik yang dilakukan oleh lembaga independen. Dengan demikian integrasi pemikiran Simon dan Ostrom memperkaya analisis principal–agent. Simon menekankan rasionalitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan birokrasi, sedangkan Ostrom menyoroti pentingnya partisipasi dan desentralisasi kontrol. Kedua perspektif ini sama-sama berfungsi untuk menutup celah asimetri informasi dan mencegah moral hazard dari pihak agent. Jika diterapkan dalam konteks Indonesia, misalnya pada pengelolaan dana transfer daerah dan dana desa, pendekatan Simon dapat mendorong penggunaan sistem informasi berbasis data (transparansi digital), sementara pendekatan Ostrom dapat memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengawasan dana desa. Sinergi keduanya akan menciptakan tata kelola keuangan publik yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif, sekaligus mengurangi peluang penyalahgunaan oleh agent.
Upaya meminimalisir penyimpangana agent
Untuk mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan publik penting dilakukan reformasi kelembagaan dan penguatan mekanisme pengawasan. Pertama, melalui penerapan transparansi digital melalui instrumen seperti e-budgeting dan e-procurement dapat memperkecil kesenjangan informasi antara agent dan principal. Kedua melalui keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran dan pengawasan publik perlu diperluas agar principal dapat berperan lebih aktif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pemanfaatan Open Government Indonesia (OGI). Ketiga melalui penguatan peran lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman menjadi penting dalam mencegah sekaligus menindak penyalahgunaan anggaran serta keterlibatan LSM dalam advokasi anggaran, serta pemanfaatan Open Government Indonesia (OGI).
Penutup
Pengelolaan keuangan publik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tantangan praktik korupsi yang berakar pada relasi principal–agent. Teori ini menunjukkan bahwa ketidakselarasan kepentingan, asimetri informasi, dan lemahnya mekanisme pengawasan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh birokrat maupun pejabat publik. Upaya reformasi melalui transparansi, akuntabilitas, digitalisasi anggaran, serta partisipasi masyarakat telah menjadi langkah penting untuk mempersempit ruang penyimpangan. Namun efektivitasnya bergantung pada konsistensi implementasi, kualitas pengawasan independen, dan keterlibatan aktif publik. Dengan demikian, penguatan tata kelola keuangan negara berbasis ilmu, data, serta prinsip pemerintahan terbuka menjadi fondasi strategis dalam mencegah korupsi dan mewujudkan birokrasi yang benar-benar melayani rakyat.
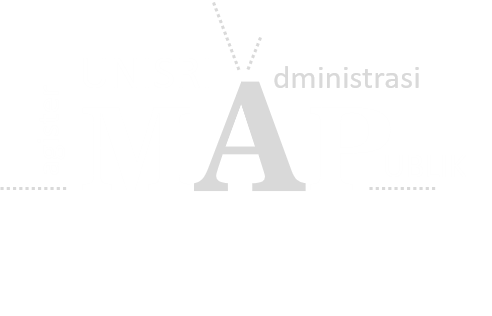


Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.