Akhir-akhir ini publik kerap menyaksikan kebijakan pemerintah yang secara administratif “benar”, tetapi secara sosial dan moral menimbulkan kegelisahan. Penggusuran dinyatakan sah, digitalisasi layanan dinilai efisien, proyek infrastruktur dianggap sukses namun suara warga terdampak sering kali tenggelam. Di sinilah persoalan mendasarnya, kebijakan publik semakin rapi secara prosedural, tetapi kering secara refleksi dan etika. Fenomena ini menandai krisis “diam-diam” dalam manajemen publik modern. Pemerintah tidak kekurangan aturan, indikator kinerja, maupun sistem pengawasan. Yang justru langka adalah ruang refleksi etis akan kesediaan negara untuk bertanya, “Apakah kebijakan ini adil?”, “Siapa yang dirugikan?”, dan “Apakah tujuan publik benar-benar tercapai, bukan sekadar terlaporkan?”
Dari Manajemen Efisien ke Pemerintahan Reflektif
Dalam literatur administrasi publik kontemporer, muncul pendekatan yang dikenal sebagai Reflexive–Ethical Public Management (REPM). Pendekatan ini menolak pandangan bahwa tugas pemerintah cukup berhenti pada kepatuhan prosedur dan pencapaian target angka. Sebaliknya, REPM menempatkan reflektivitas dan etika sebagai inti pengelolaan pemerintahan.
Reflektivitas berarti kemampuan pemerintah untuk secara sadar mengkaji ulang asumsi, nilai, dan dampak kebijakan bukan setelah masalah meledak, tetapi sejak kebijakan dirancang. Etika publik menuntut negara tidak hanya bertanya “boleh atau tidak”, melainkan “pantas atau tidak”, “adil atau tidak”, dan “bermanfaat bagi siapa”. Pendekatan ini relevan di tengah kompleksitas kebijakan saat ini mulai dari penggunaan kecerdasan buatan dalam layanan publik, pengelolaan aset negara sebagai instrumen investasi, hingga kebijakan lingkungan yang berdampak langsung pada ruang hidup warga.
Partisipasi yang Ramai, tetapi Sunyi Makna
Ironisnya, di tengah jargon partisipasi publik yang kian sering diulang, praktik di lapangan menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Forum konsultasi publik berlangsung, survei kepuasan digelar, dan aspirasi dicatat. Namun, publik jarang tahu sejauh mana suara mereka benar-benar memengaruhi keputusan akhir. Inilah yang oleh banyak pengamat disebut sebagai partisipasi kosmetik yang berarti ramai secara prosedur, tetapi sunyi secara substansi. Dalam kerangka REPM, kondisi ini menunjukkan kegagalan reflektif. Pemerintah hadir mendengar, tetapi tidak sungguh-sungguh merefleksikan makna dari apa yang didengar.
Teknokrasi yang Melaju Lebih Cepat dari Etika
Percepatan digitalisasi pemerintahan menjadi contoh paling nyata. Sistem penilaian otomatis, big data, dan algoritma kebijakan digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Namun, diskursus tentang keadilan algoritmik, perlindungan data warga, dan bias kebijakan digital masih tertinggal jauh. Kebijakan bergerak cepat, sementara refleksi etis berjalan tertatih. Akibatnya, publik sering kali baru menyadari dampak kebijakan setelah kerugian sosial muncul mulai dari eksklusi kelompok rentan hingga hilangnya ruang deliberasi publik. Di sinilah gap utama fenomena terkini terkait kapasitas teknis birokrasi tumbuh pesat, tetapi kapasitas reflektif dan etisnya stagnan.
Beban Moral yang Terlalu Berat di Pundak Birokrat
Dalam praktik sehari-hari, etika sering direduksi menjadi urusan integritas individu aparatur. Ketika terjadi pelanggaran, yang disorot adalah moral personal, bukan sistem yang membentuk keputusan tersebut. Padahal, tanpa ruang refleksi kelembagaan seperti evaluasi kebijakan berbasis nilai dan dialog etika lintas sektor birokrat bekerja dalam sistem yang miskin panduan moral. REPM justru menekankan bahwa etika publik bukan sekadar soal orang baik dalam sistem buruk, melainkan sistem yang secara sadar dirancang untuk memungkinkan keputusan etis.
Menuju Pemerintahan yang Tidak Sekadar Benar, tetapi Juga Adil
Dalam konteks Indonesia, pendekatan Reflexive–Ethical Public Management menjadi semakin mendesak. Pemerintahan dihadapkan pada tekanan pembangunan, tuntutan investasi, serta ekspektasi publik yang terus meningkat. Tanpa refleksi etis, kebijakan mudah tergelincir menjadi legalistik tetapi tidak legitim. REPM mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari laporan kinerja, tetapi dari rasa keadilan yang dirasakan warga. Negara bukan sekadar manajer proyek, melainkan penjaga nilai publik. Jika tidak, kita akan terus menyaksikan paradoks kebijakan akan benar di atas kertas, tetapi bermasalah di kehidupan nyata.
Penutup
Pada akhirnya, persoalan terbesar dalam kebijakan publik hari ini bukan semata kekurangan regulasi atau lemahnya kapasitas teknis negara. Yang lebih mengkhawatirkan adalah menyempitnya ruang nurani dalam pengambilan keputusan publik. Ketika kebijakan hanya diukur dari kepatuhan prosedur dan capaian indikator, negara berisiko kehilangan kemampuan untuk merasakan dampaknya bagi warga.
BMD dalam Perspektif Tata Kelola Publik Modern
Dalam kerangka good governance dan public asset management, aset publik dipandang sebagai capital base pembangunan daerah. Artinya, BMD bukan sekadar milik pemerintah, tetapi amanah publik yang harus dioptimalkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menuntut perubahan mindset dari compliance-based management menuju value-based management. Pengelolaan BMD tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi (Permendagri 19/2016 dan turunannya), tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Masalah Klasik Pengelolaan Barang Milik Daerah
Berbagai studi dan laporan pemeriksaan menunjukkan bahwa persoalan BMD bersifat struktural dan berulang, antara lain:
- Aset tidak termanfaatkan secara optimal, terutama tanah dan bangunan strategis.
- Data aset yang tidak akurat, tidak sinkron antara fisik, administrasi, dan legal.
- Ketakutan birokrasi terhadap risiko hukum, sehingga memilih tidak memanfaatkan aset.
- Minimnya kapasitas perencanaan bisnis aset di tingkat OPD.
- Absennya integrasi antara perencanaan pembangunan dan portofolio aset daerah.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan BMD bukan semata teknis, melainkan menyangkut tata kelola, kepemimpinan, dan orientasi kebijakan.
Aset Daerah sebagai Instrumen Investasi
Dalam perspektif investasi publik, BMD dapat berperan sebagai:
- Underlying asset untuk kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga.
- Leveraging instrument untuk menarik investasi swasta.
- Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.
- Pemicu pengembangan kawasan ekonomi baru.
Skema seperti Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG) merupakan bentuk konkret transformasi aset menjadi investasi. Namun, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada kualitas analisis kelayakan dan tata kelola keputusan.
Implikasi Kebijakan dan Kelembagaan
Reorientasi BMD sebagai instrumen investasi membawa implikasi penting:
- Diperlukan unit atau fungsi manajemen aset yang profesional, bukan sekadar administratif.
- Integrasi BMD ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD).
- Penguatan kapasitas SDM dalam analisis bisnis, investasi, dan risiko.
- Kepemimpinan kepala daerah sebagai asset champion yang berani mengambil keputusan strategis dengan mitigasi risiko yang memadai.
- Penguatan transparansi dan partisipasi publik untuk menjaga legitimasi pemanfaatan aset.
Penutup
Barang Milik Daerah menyimpan potensi besar sebagai instrumen investasi dan pengungkit pembangunan daerah. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan jika terjadi perubahan paradigma, dari aset sebagai beban administratif menuju aset sebagai modal pembangunan. Transformasi ini bukan sekadar soal regulasi, melainkan soal keberanian kebijakan, kualitas tata kelola, dan kecakapan manajerial pemerintah daerah.
Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi nilai, BMD dapat menjadi fondasi kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
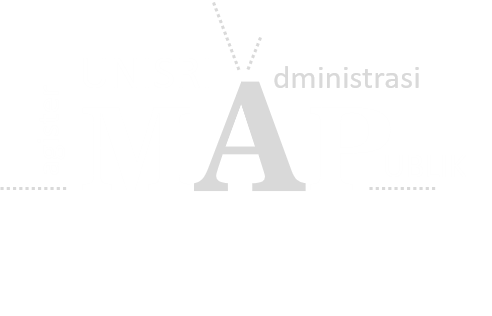


Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.