Dalam beberapa tahun terakhir, diskursus kebijakan publik di Indonesia menghadapi situasi yang semakin kompleks bukan hanya karena persoalan klasik seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang lamban, atau ketimpangan pembangunan, tetapi juga karena munculnya fenomena baru dalam ruang digital yaitu post-truth. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika fakta objektif tidak lagi menjadi rujukan utama dalam pembentukan opini publik, melainkan digantikan oleh narasi emosional, keyakinan personal, dan informasi yang disajikan secara manipulatif. Dalam konteks kebijakan publik, fenomena ini menjadi tantangan serius karena kebijakan bekerja dengan logika rasional, sementara post-truth bekerja dengan logika emosi. Saat ini Kita hidup dalam sebuah masa ketika yang terdengar meyakinkan lebih dipercaya daripada yang benar.
Ketika Data Bertarung dengan Narasi
Dalam tradisi kebijakan publik modern, data dan analisis menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan keputusan yang efektif dan berorientasi solusi. Namun dalam era post-truth, data sering kali kalah cepat dalam pertarungan persepsi. Fakta harus bersaing dengan judul berita yang menggugah emosi, narasi viral di media sosial, potongan video yang dipersepsikan sebagai “bukti”, dan interpretasi personal yang diperlakukan seolah-olah setara dengan riset ilmiah. Fakta tidak hilang, tetapi posisinya terdegradasi. Nilai kebenaran bergeser menjadi “kebenaran yang dirasakan”.
Mengapa Post-Truth Berbahaya bagi Kebijakan Publik?
- Memecah Rasionalitas Publik
Post-truth menggerus kemampuan masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan dengan kerangka berpikir yang rasional. Debat publik lebih sering berpindah dari substansi kebijakan ke isu personal, simbolik, atau politisasi identitas.
- Membangun Tekanan Politik yang Salah Arah
Ketika emosi menjadi motor penggerak opini publik, tekanan sosial yang muncul bukanlah tekanan untuk memperbaiki kebijakan, melainkan untuk memuaskan sentimen kolektif. Akibatnya, pemerintah rentan mengambil keputusan reaktif demi meredam polemik, bukan untuk menjawab akar masalah.
- Menghambat Komunikasi Kebijakan
Dalam isu kesehatan, lingkungan, atau sosial, pemerintah sering kali kesulitan menyampaikan data secara efektif. Mis/disinformasi bekerja jauh lebih cepat, sementara klarifikasi dianggap membosankan atau dianggap “mengada-ada”. Di masa pandemi, kita menyaksikan bagaimana hoaks mampu mengganggu efektivitas kebijakan vaksinasi. Bukti ilmiah seringkali tidak mampu menandingi narasi emosional yang lebih sederhana, lebih pendek, dan lebih viral.
Apa yang Menyuburkan Post-Truth?
Beberapa faktor menjelaskan mengapa post-truth mudah berkembang:
1. Informasi berlimpah, literasi tak seimbang
Kemudahan akses informasi tidak serta merta diiringi kemampuan publik untuk memilah, mengkritisi, dan mengonfirmasi.
2. Algoritma media sosial yang memperkuat bias
Platform digital cenderung menyajikan konten yang sesuai minat dan emosi pengguna. Ini menciptakan echo chamber dan mempersempit ruang dialog rasional.
3. Turunnya kepercayaan pada institusi
Ketika pemerintah, lembaga hukum, dan media arus utama dianggap tidak netral, publik mencari “kebenaran alternatif” yang sering kali tidak berbasis fakta.
Menguatkan Ketahanan Kebijakan di Era Post-Truth
Menghadapi era ini, ada beberapa strategi yang dapat diperkuat:
- Mendorong evidence-based policy
Kebijakan harus didasari data, evaluasi, dan kajian ilmiah, bukan tekanan opini publik jangka pendek.
- Mengembangkan kemampuan komunikasi kebijakan yang efektif
Bahasa akademis harus diterjemahkan menjadi narasi yang relevan, sederhana, dan mudah dipahami publik.
- Membangun literasi digital masyarakat
Penguatan literasi digital menjadi prasyarat penting dalam melindungi publik dari misinformasi.
- 4. Memperkuat transparansi dan keterbukaan data
Ketika data mudah diakses, ruang bagi disinformasi akan mengecil.
Penutup Post-truth adalah tantangan kontemporer yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam perumusan kebijakan publik. Ketika narasi emosional mendominasi ruang digital, rasionalitas publik tergerus dan proses kebijakan menjadi rentan. Namun, dengan memperkuat literasi, transparansi, dan komunikasi kebijakan yang baik, kita dapat membangun ruang publik yang lebih sehat, ruang di mana fakta kembali mendapat tempat terhormatnya, dan kebijakan publik dapat bekerja sesuai tujuan dasarnya dalam menghadirkan solusi bagi masalah-masalah masyarakat.
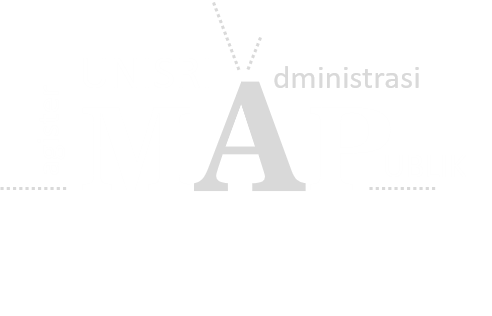


Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.